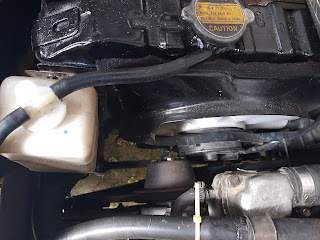AHAD,
6 FEBRUARI
Pagi
hari Ahad tak ubahnya Sabtu malamnya, masih lanjut ngobrol, tempat
yang sama, seolah-olah itu kelanjutan tadi malam yang dipisahkan oleh
fase tidur sebentar. Masih di tempat Hariri, kali ini datang
tambahan: Pak Muqiet dan Pak Taufiq. Mereka menemani saya ngobrol
pagi itu. Betapa terhormatnya sampai-sampai saya merasa rikuh.
Obrolannya tidak serius, melainkan haha dan hihi. Itulah tema
kesukaan kami semua.
Setelah
disuguhi sarapan yang lebih tampak sebagai prasmanan besar di malam
hari atau gala
dinner,
saya
pamit, tapi masih dicegat oleh Pak Muqiet.

“Tolong
mampir ke rumah meski sebentar.”
“Tapi,
saya agak terburu-buru,” kelit saya.
“Sebentaaar
saja, berdiri di depan pintu pun tidak apa-apa. Yang penting,
kunjungi rumah kami, sebentar saja supaya kami juga dapat berkah yang
dibawa tamu.”
Undangan
dipenuhi dengan syarat tak lebih dari secangkir kopi. Sewaktu kami
ngobrol (lagi) di kediaman mantan Wakil Bupati Jember tersebut, eh,
ternyata, di belakang, mobil saya dicucikan. Seorang lelaki paruh
baya tampak menyemprotkan air dan mengelap bodi mobil. Waduh, ini
jebakan, tapi asyik juga, sih. Rupanya, begitulah cara beliau membuat
kejutan.
Dari
Karangharjo, saya menuju Sempolan, pertigaan jalan raya
Jember-Banyuwangi. Saya ikat janji dengan Kak Fadlillah di sana. Pas!
Kami bertemu dan hanya sebentar dalam selisih waktu. Sebetulnya, saya
juga ingin mampir di Suren untuk bertandang ke rumah Lora Miftah,
tapi kata kabar tersiar, beliau kurang sehat dan masih butuh
istirahat. Jadi, rencana bertemu dengan beliau gagal
ditunda.
Dari
situ, kami meluncur ke timur, menuju perkebunan pinus di Garahan
untuk menghadiri kopdar Triwulan Komunitas Colt Jember (JCL).
Istilahnya, sekalian mampir mumpung saya memang hendak melintasi
Gumitir.

Kopdar
Colt JCL ini, kabarnya, dilaksanakan tiap tiga bulan sekali. Tapi,
selama dua tahun terakhir kosong karena pandemi. Untuk kopdar pertama
setelah lama diem-dieman,
mereka buat pengumuman di Facebook. Saya menyatakan bersedia hadir
karena memang ada rencana ke Jawa. Hukum “sekalian” dan “mumpung”
pun berlaku. Eman-eman jika datang untuk satu kepentingan padahal
bisa nambah untuk kepentingan yang lain. Maka, saya ikut pepatah:
“sekali ngegas dua-tiga kota terlampaui”.
Dalam
acara itu, hadir teman-teman Jogja, Kediri, Malang, juga Surabaya.
Lainnya saya kurang tahu. Tapi, yang paling banyak jelaslah yang dari
Jember dan Banyuwangi, kebanyakan mobil bak terbuka. Acara resminya
sebetulnya tidak lama, satu jam tak sampai. Tapi, orang-orang tidak
segera bubar. Sebagian menyelenggarakan rapat untuk acara mendatang,
sebagian lagi mandi, atau bersepada, atau main ATV (memang ada
persewaannya, termasuk anak saya ikut main). Sebagian lagi entah pada
ngapain saja. Entahlah.
Sekitar
pukul 13.00 lewat, saya meninggalkan lokasi, berbarengan dengan
beberapa mobil yang keluar. Rombongan Jogja sudah pergi dari tadi.
Saya belok kiri, yang lain belok kanan.
Tak
jauh dari tempat itu, Colt langsung menghadapi tanjakan mengular,
Gunung Gumitir. Ini jalan memang paling asyik suasananya. Tapi,
sekarang tidak seserem dulu. Waktu kecil, saya sering lewat jalan
ini, ketika kendaraan tak seramai sekarang. Dulu, kalau malam,
mobil-mobil yang mau melintasi hutan ngumpul lebih dulu di Garahan.
Setelah ada beberapa, baru mereka konvoi lalu mulai jalan
bersama-sama. Kenapa begitu, adakah mereka takut hantu hutan atau
takut perampok, wallahu a’lam.
Lepas
hutan, masuk Kalibaru. Dari spion kanan, tampak ada dua Colt yang
membuntuti. Saya sein kiri supaya mereka menyalip, namun mereka tetap
di belakang. Akhirnya, saya paham. Rupanya, mereka mengawal,
mengiringi. Dan ketika saya telah tiba di tempat persinggahan,
Majlisus Sa’adah, Wadung, Glenmore, untuk menyambangi sepupu saya,
tiba-tiba Colt station berhenti juga (yang pikap lanjut). Loh,
ternyata, yang nongol adalah Mas Agus Supriady (beliau ini beberapa
kali membeli buku sama saya). Maka, terjadilah perbincangan sekejap.
Lain waktu, saya ingin bincang lebih lama dengan dia, tidak di tepi
jalan, tapi di suatu tempat yang lebih nyaman. Kapan itu? Saya tidak
tahu.
“Cik,
aku cuman mau numpang tidur sejenak, ndak usah repot-repot,” kata
saya pada si sepupu yang perannya saat itu adalah sebagai tuan rumah.
Itu ucapan serius, bukan basi-basi.
“Iya,
Kak, silakan,” jawab si Locik yang bernama asli Yazid lebih datar
lagi.
Tapi
setelah kurang lebih satu jam tidur, saya bangun dan tiba-tiba saya
melihat makanan yang sudah disediakan. Basa-basi gagal, ternyata saya
diperlakukan sebagai tamu beneran. Ya, terlanjur ada, diembatlah itu
si nasi dan si ikan dan si lauk-pauk lainnya.
Dan
seperti yang sudah saya sampaikan di awal kedatangan, sesuai S.O.P,
saya langsung pamit pergi, melanjutkan perjalanan ke timur. Masih ada
dua titik persinggahan yang harus disamperi, padahal rencana pulang
ke Madura adalah malam nanti? Mungkinkah?

“BustanulMakmur II itu masuk ke utara,
Kak,” kata Yazid yang saya panggil Locik.
“Ke
utara di mana?”
“Pokoknya,
nanti setelah sampai Genteng, Kak Izi bakal ketemu dengan tiga lampu
merah. Nah, setelah lampu merah yang ketiga itu ada jalan masuk ke
utara, belok kiri. Letaknya di belakang kampus Ibrohimi.”
“Baik,
pasti ketemu.”

Tujuan
ke Bustanul Makmur adalah untuk mengunjungi Rifki dan adiknya, Afthon
Dhani. Kedua saudara ini adalah sepupu persis almarhumah istri saya
(juga famili saya). Keduanya sedang menjalani guru tugas dan desainer
di pondok yang didirikan oleh Kiai Saifuddin tersebut. Sore itu,
Dhani sedang ngajar dan Kiki sedang keluar. Saya menunggu. Setelah
bertemu Dhani, baru Kiki datang menjelang maghrib. Kejutan baru
terjadi. Ternyata Kiki—panggilan Rifki—baru pulang dari Bustanul
Makmur Pusat. Dia mengatakan bahwa saya sempat dirasani Gus Endi.
Terpancing oleh itu, akhirnya kami pergi ke sana.

Maka,
bertemulah kami di Bustanul Makmur Pusat yang ternyata memang merupakan kediaman Gus Endi. Saya bertemu beliau
di Buleleng, dua tahun lalu, di rumah sepupu beliau, pamanda Ahmadul
Faqih Mahfudz (yang secara nasab merupakan sepupu Gus Endi dari jalur
ayahnya; merupakan paman saya dari jalur ibu saya yang nyambung
melalui embah putrinya. Tapi, Gus Endi ternyata bukan paman saya
karena beliau berada di jalur nasab yang berbeda). Di sana, kami juga
bertemu dengan Gus Imdad dan Gus Nawal serta seorang temannya dari
Jember. Pertemuan yang kurang tepat secara waktu—karena habis
maghrib—itu sangat gayeng sehingga sempat membuat saya lupa diri,
lupa bahwa masih ada satu titik tersisa yang harus disingghi.
Karena
saya tidak menggunakan Google Maps, maka saya tidak bisa
memperkirakan jarak. Makanya, saya terkaget-kaget karena ternyata
rute Genteng – Banyuwangi itu sangat jauh, lebih-lebih malam itu
gerimis dan jalan sangat padat, ditambah rutenya tidak akrab. Begitu
membosankan, tapi saya jalani saja dengan santai. Bonusnya adalah
salah jalan di Banyuwangi. Saya sempat muter-muter beberapa kali dan
baru berhasil mengakses kembali Jalan Nasional ke arah Ketapang
setelah buang jarak dan buang waktu kurang lebih 15 menit lamanya.
Itu buang-buang jika mengingat saya sedang kejar waktu ingin sowan ke
Kiai Fadlurrahman, tapi itu juga tambahan pengalaman sebab akhirnya
saya jadi tahu tempat-tempat yang semua tidak pernah saya lewati.
Terus,
bagaimana cara saya agar tahu jalan masuk ke pondok pesantren asuhan
Kiai Fadol (panggilan masyarakat terhadap Kiai Fadlurrahman Zaini)
itu sementara congap (pertigaan jalan masuk)-nya sangat tersembunyi?
Yang saya lakukan adalah menelepon adik agar mengecek jarak dari
Pelabuhan Ketapang ke congap yang mengarah ke pondok beliau, PP
Al-Abror Ar-Robbaniyun.
“18
kilometer,” katanya.
“Pas?”
“Iya.”
Saya
pun menginjak gas tanpa ragu dan baru kembali memperhatikan
pergerakan odometer mobil setelah odo mencapai 17 km. Setelahnya,
barulah saya mencari jalan masuk ke arah kanan, ke timur, ke arah
pondok, eh, ternyata masih larat juga. Masih untung ada tukang sate
yang menyelamatkan. Saya bertanya kepadanya. Kata dia, saya kelewatan
sekitar hampir satu kilometer. Barangkali, tukang sate itu sudah lama
sekali tidak bertemu dengan orang yang bertanya lokasi karena
orang-orang pada pakai aplikasi (setelah tiba di rumah dan menulis
catatan perjalanan ini, saya cek di Google Maps melalui PC, ternyata
jarak dari pintu pelabuhan Ketapang ke congap itu cuman 16 kilometer.
Adik saya sepertinya salah paham karena angka 18 kilometer tersebut
adalah jarak dari pintu pelabuhan ke pondok Nurul Abrorar-Robbaniyyin, bukan ke
congap).
Sowan
ke Kiai Fadlurrahman Zaini di malam itu gagal. Kata petugas,
sepertinya waktu sudah kemaleman untuk bertamu. Jam menunjuk 21.30.
Memang iya, sih. Mereka memberi saran agar kami bermalam. Saya
berterima kasih karena itu tidak mungkin. Tak apa-apa, semoga lain
waktu kami bisa ke situ. Sebelum pergi, sempat terlintas kenangan
terakhir di tempat itu bersama mendiang istri saya, melintasi
khayalan. Saya ingat sowan terakhir kami dua tahun yang lalu. Di
sana, kami disambut dengan penuh kehangatan (dan ...ah, tapi saya
jadi sedih).
Perjalanan
diteruskan ke Arjasa setelah kami singgah sejenak di sebuah kedai, di
Galekan. Menghubungi nomor Moeftin Nadzir tapi tak aktif, ya sudah,
lanjut saja. Hujan lumayan deras. Sempat saya gelagapan di dalam
hutan Baluran. Saya deja vu, ingat kejadian serupa 12 tahun yang
lalu. Tapi, kali ini lebih mencekam karena dua kali lampu depan mati
mendadak lalu hidup kembali. Kak Fadlillah mengaku cemas atas
kejadian itu (tapi ia sampaikan setelah tiba di Madura). Mungkin,
mati lampu dianggap isyarat kurang baik. Tapi, bagi saya tidak karena
saya tahu persoalannya. Kejadian mati lampu mendadak memang sudah
terjadi sebelumnya, beberapa kali, tapi belum ketemu masalahnya. Baru
setiba di Asembagus lah saya tahu. Ternyata, penyakitnya adalah
penjepit sekring tabung goyah, bukan relay lampu yang karatan seperti
yang saya duga sebelumnya.
Akhirnya,
saya tiba di Arjasa dalam keadan penat tak berdaya. Rencana mau
lanjut malam itu juga digagalkan. Sebetulnya, saya bisa tidur
sejenak, bangun, dan langsung berangkat. Tapi, bukan itu alasannya,
bukan capeklah alasan terbesarnya, melainkan karena saya tak ingin
pagi esoknya anak saya bangun dan menemukan saya tak ada lagi dari
sisinya.
“Besok
saja, Kak,” kata saya pada Kak Fadlillah.